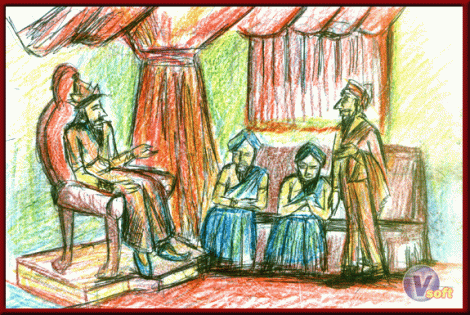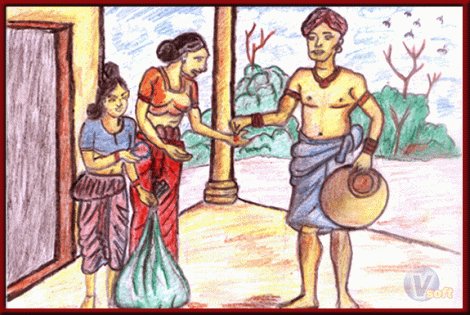picture source: www.jathakakatha.org
APANNAKA JATAKA: MELINTASI PADANG GURUN (JATAKA 1)
Pada suatu hari, ketika Buddha Gotama sedang berdiam di Vihara Jetavana dekat kota Savatthi, seorang saudagar kaya raya, bernama Anathapindika datang menemuiNya untuk memberi hormat. Pelayan-pelayannya membawa banyak rangkaian bunga, wewangian, mentega, minyak, madu, sirup gula, pakaian dan jubah. Anathapindika kemudian bersujud kepada Buddha, mempersembahkan persembahan yang telah dibawanya, dan duduk dengan penuh hormat. Pada waktu itu, Anathapindika ditemani pula oleh lima ratus teman-temannya yang adalah pengikut guru-guru yang sesat. Teman-teman Anathapindika juga turut memberikan penghormatan pada Buddha dan kemudian duduk di dekat saudagar kaya tersebut. Wajah Buddha tampak seperti bulan purnama dan tubuhnya diliputi oleh cahaya aura. Duduk di atas batu merah, Buddha terlihat seperti seekor singa muda yang mengaum dengan suara yang jelas dan mulia, ketika Beliau memberikan mereka sebuah khotbah yang begitu indah dan manis untuk didengar.
Setelah mendengar ajaran Buddha, kelima ratus teman Anathapindika meninggalkan praktek keliru mereka dan mengambil perlindungan dalam Tiga Mustika: Buddha, Dhamma dan Sangha. Setelah itu, dengan konsisten mereka datang bersama Anathapindika untuk mempersembahkan bunga dan dupa dan untuk mendengarkan Dhamma. Mereka memberikan persembahan secara sukarela, menjalankan sila, dan dengan setia melaksanakan latihan di Hari
Uposatha 1. Namun segera setelah Buddha meninggalkan kota Savatthi untuk kembali ke Rajagaha, orang-orang ini mulai meninggalkan keyakinan baru mereka dan kembali pada keyakinan lama mereka masing-masing.
Sekitar tujuh atau delapan bulan kemudian, Buddha kembali mengunjungi Jetavana. Dan lagi, Anathapindika membawa teman-temannya untuk mengunjungi Buddha. Mereka memberikan penghormatan mereka, tetapi Anathapindika kemudian menjelaskan bahwa mereka telah melupakan perlindungan mereka dan telah kembali pada praktek-praktek lama mereka.
Buddha Gotama kemudian bertanya, “Apakah benar bahwa kamu telah meninggalkan perlindungan dalam Tiga Mustika demi perlindungan dalam ajaran lain?” Suara Buddha begitu luar biasa jelas karena selama banyak (tak terhitung) kalpa Beliau telah menyatakan hanya kebenaran.
Ketika orang-orang ini mendengar pertanyaan tersebut, mereka tidak dapat menyangkal kebenaran. “Ya, Yang Mulia,” mereka mengakuinya. “Itu benar.”
“Murid-muridKu,” Buddha berkata, “tidak di antara neraka terendah maupun surga termulia, tidak ada di dalam dunia-dunia yang tidak terbatas yang membentang di kanan dan kiri, yang sebanding atau lebih unggul dari seorang Buddha. Sesungguhnya tidak terhitung manfaat dari menjalankan sila dan melakukan perbuatan bersahaja lainnya.”
Kemudian Beliau menyatakan kemuliaan Tiga Mustika. “Dengan mengambil perlindungan dalam Tiga Mustika,” Buddha berkata pada mereka, “seseorang akan terhindar dari kelahiran kembali dalam keadaan yang sengsara.” Buddha lebih jauh menjelaskan bahwa meditasi tentang Tiga Mustika akan membawa pada pencapaian empat tingkatan Pencerahan.
“Mencari perlindungan seperti ini,” Buddha menegur mereka, “kalian pastilah telah melakukan suatu hal yang keliru. Di masa lalu, juga, orang-orang yang salah mengambil perlindungan sebagai perlindungan sejati menemui bencana. Sebenarnya mereka menyembah para yakkha – roh jahat – di padang gurun dan mereka benar-benar hancur. Sebaliknya, orang-orang yang memegang kebenaran tidak saja bertahan, tetapi mereka berhasil mencapai kemakmuran di padang gurun yang sama itu.”
Anathapindika mengangkat tangannya, memuji Buddha, dan bertanya padaNya untuk berkenan menceritakan kisah masa lalu tersebut.
“Demi menghilangkan ketidakacuhan dunia dan demi mengalahkan penderitaan,” Buddha berkata, “Aku melatih Sepuluh Kesempurnaan selama berkalpa-kalpa lamanya. Dengarkanlah baik-baik dan Aku akan bercerita.”
Mendapatkan perhatian penuh dari mereka yang hadir waktu itu, Buddha dengan jelas, seolah-olah menyingkapkan bulan purnama dari balik awan, apa yang kelahiran kembali telah tutupi dari mereka.
Jauh di masa lampau, ketika Brahmadatta memerintah di Baranasi, Bodhisatta terlahir sebagai anak seorang pedagang dan tumbuh besar sebagai seorang pedagang yang bijaksana. Pada waktu yang sama pula, di kota yang sama, terdapat pula pedagang lain yang sangat bodoh, tanpa akal sehat sama sekali.
Pada suatu hari, kedua pedagang itu, masing-masing membawa lima ratus kereta penuh dengan barang-barang mahal dari Baranasi, bersiap pergi meninggalkan kota dengan arah yang sama dan waktu yang sama pula. Pedagang bijaksana tersebut berpikir, “Jika pedagang bodoh ini pergi bersama denganku dan jika seribu kereta kami jalan bersama, akan terlalu banyak untuk sebuah perjalanan. Mencari kayu dan air untuk orang-orang akan menjadi sulit dan tidak akan ada cukup rumput untuk lembu-lembu. Entah aku atau dia yang harus pergi terlebih dahulu.”
“Lihat,” dia berkata pada pedagang lainnya, “kita berdua tidak dapat pergi bersama. Apakah kamu atau aku yang pergi terlebih dahulu?”
Pedagang bodoh tersebut berpikir, “Akan ada banyak keuntungan bila aku pergi terlebih dahulu. Aku akan melewati jalan yang masih asri. Lembu-lembuku akan memiliki cukup rumput. Orang-orangku akan mendapatkan dedauanan yang terbaik untuk masakan kari. Air masih asli dan tidak terganggu. Terbaik dari semua itu, aku akan bisa mendapatkan harga terbaik untuk barang-barang daganganku.” Mempertimbangkan semua keuntungan itu, dia berkata, “Aku akan pergi terlebih dahulu, temanku.”
Bodhisatta senang mendengar hal itu karena ada banyak keuntungan apabila pergi sesudahnya. Dia beralasan, “Kereta-kereta yang pergi terlebih dahulu akan meratakan tanah yag tidak rata dan aku akan bisa melintasi jalan yang sudah rata tersebut. Lembu-lembu mereka akan memakan rumput-rumput tua dan lembu-lembuku akan memakan rumput-rumput muda manis yang baru tumbuh di sepanjang perjalanan itu. Orang-orangku akan menemukan dedaunan muda manis untuk kari karena yang tua sudah dipetik. Apabila di tempat yang tidak ada airnya, rombongan pertama akan harus menggali untuk persediaan mereka dan kami akan dapat minum dari sumur yang sudah mereka gali tersebut. Tawar-menawar harga adalah pekerjaan yang melelahkan: dia akan melakukan hal itu dan aku akan bisa melakukan penawaran berdasarkan harga yang sudah dipatoknya.”
“Sungguh bagus, temanku,” dia berkata, “silakan pergi terlebih dahulu.”
“Ya, aku akan pergi terlebih dahulu,” kata pedagang bodoh tersebut dan dia mempersiapkan keretanya dan pergi terlebih dahulu. Setelah beberapa lama dia pergi ke pinggiran hutan untuk mengisi kendi-kendi air besar miliknya sebelum pergi melintasi padang pasir sepanjang enam puluh
yojana 2 yang terbentang di depannya.
Yakkha yang berdiam di padang gurun tersebut sudah mengamati rombongan tersebut. Ketika rombongan tersebut mencapai tengah padang gurun, dia menggunakan kekuatan magisnya untuk menciptakan sebuah kereta indah yang ditarik oleh lembu-lembu muda berwarna putih. Dengan iringan selusin yakkha sambil membawa pedang dan perisai, dia mengendara bersama keretanya selayaknya seorang dewa. Rambut dan pakaiannya basah dan dia memiliki untaian teratai biru dan bunga lili putih di kepalanya. Para pelayannya juga basah semua dan memiliki untaian bunga. Bahkan lembu-lembunya memiliki ladam dan roda-roda keretanya berlumpur.
Ketika angin dating dari arah depan, si pedagang melaju ke depan rombongan untuk menghindari debu yang terbang ke belakang rombongan. Yakkha kemudian menarik keretanya mendekati si pedagang dan mengucapkan salam dengan ramah. Si pedagang membalas salam dan menarik keretanya ke salah satu sisi sehingga memungkinkan kereta-keretanya melintas terlebih dahulu sedangkan dia dan yakkha dapat berbincang.
“Kami dalam perjalanan kami dari Baranasi,” jelas si pedagang. “Aku melihat semua orang-orangmu basah dan berlumpur dan kamu memiliki teratai dan lili di kepalamu. Apakah hujan turun sesaat ketika kamu melintasi jalan ini? Apakah kamu melewati kolam yang penuh dengan teratai dan bunga lili?”
“Apa yang kamu maksud?” tanya yakkha. “Di sebelah sana terdapat sebuah hutan yang lebat. Di dalamnya terdapat air yang berlimpah. Disana selalu hujan dan disana terdapat banyak danau-danau dengan bunga teratai dan lili.” Kemudian, berpura-pura tertarik dengan bisnis si pedagang, dia bertanya, “Apa yang kamu miliki di keretamu?”
“Barang-barang mahal,” jawab si pedagang.
“Apa yang ada di dalam kereta ini yang kelihatannya sangat berat?” tanya yakkha ketika kereta terakhir melintas.
“Kereta itu penuh berisi air.”
“Kamu sungguh bijaksana membawa air bersamamu sejauh ini tetapi itu tidaklah perlu sekarang ini karena air sungguh berlimpah ruah di depan sana. Kamu dapat melakukan perjalanan lebih cepat dan ringan tanpa kendi-kendi berat penuh air itu. Lebih baik kamu memecahkan kendi-kendi tersebut dan membuang air di dalamnya. Baiklah, selamat jalan,” dia berkata demikian sembari menarik keretanya sendiri menjauh. “Kami akan pergi ke tujuan kami sendiri. Kami sudah lama berhenti disini.” Dia pergi bersama pengikutnya dengan cepat. Segera setelah mereka pergi dari pandangan, dia berbalik dan pergi menuju kota tujuannya sendiri.
Si pedagang itu ternyata cukup bodoh untuk mengikuti saran yakkha itu. Dia memecahkan semua kendi air tanpa menyisakan satupun kendi berisi air dan memerintahkan orang-orangnya untuk melintas dengan cepat. Tentu saja mereka tidak menemukan air dimanapun dan mereka dengan segera merasakan kehausan. Ketika matahari mulai terbenam, mereka menarik kereta mereka membentuk posisi lingkaran dan menambatkan lembu-lembu mereka pada roda kereta, tetapi tidak ada air yang bisa diberikan untuk lembu-lembu tersebut. Tanpa air, orang-orang tidak dapat memasak nasi apapun. Mereka terjatuh kelelahan dan tertidur. Begitu malam tiba, para yakkha mulai dating menyerang, membunuh semua manusia dan hewan yang ada. Para iblis melahap daging dan menyisakan hanya tulang belulang saja, dan kemudian pergi. Tulang belulang berserakan di semua arah, tetapi lima ratus kereta masih berada disana tidak tersentuh. Demikianlah si pedagang muda bodoh tersebut menghancurkan sendiri rombongan dan pengikutnya.
Setelah enam minggu si pedagang bodoh tersebut pergi, Bodhisatta mulai bersiap dengan lima ratus keretanya. Ketika dia mencapai pinggir hutan rimba, dia pun mengisi kendi-kendi airnya. Kemudian dia mengumpulkan orang-orangnya dan berkata, “Jangan ada siapapun yang menyentuh kendi-kendi air ini tanpa seijinku. Dan juga, terdapat tanaman beracun di padang gurun ini. Jangan memakan daun apapun, bunga atau buah yang belum pernah kamu makan sebelumnya tanpa menunjukkannya padaku terlebih dahulu.” Setelah memperingatkan orang-orangnya, dia memimpin rombongannya menuju padang gurun.
Ketika mereka mencapai tengah padang pasir, yakkha muncul di jalan seperti sebelumnya. Si pedagang mengenali mata merah dan tingkah laku si yakkha yang tidak takut dan mencurigai ada sesuatu yang aneh. “Aku tahu tidak ada air di padang pasir ini,” dia berkata pada dirinya sendiri. “Apalagi orang asing ini tidak memiliki bayangan. Dia pastilah yakkha. Dia mungkin telah menipu si pedagang bodoh, tetapi dia tidak tahu seberapa cerdik diriku.”
“Pergi dari sini!” dia berteriak pada yakkha. “Kami adalah para pedagang. Kami tidak akan menyia-nyiakan air sebelum kami melihat ada air di depan kami!”
Tanpa berkata apapun, yakkha itu pergi menyingkir.
Segera setelah para yakkha itu pergi, pengikut si pedagang itu mendekati pemimpinnya dan berkata, “Tuan, orang tadi mengenakan teratai dan lili di atas kepala mereka. Pakaian dan rambut mereka basah. Mereka mengatakan pada kami bahwa di sebelah sana terdapat hutan lebat yang senantiasa turun hujan. Marilah kita membuang air kita sehingga kita dapat pergi lebih cepat dengan kereta-kereta yang lebih ringan.”
Si pedagang kemudian memerintahkan berhenti sejenak dan mengumpulkan semua orang-orangnya.
“Apakah diantara kalian ada yang pernah mendengar sebelumnya,” dia bertanya, “bahwa disana ada sebuah danau atau kolam di padang gurun ini?”
“Tidak, tuanku,” mereka menjawab. “Padang pasir ini dikenal sebagai ‘
Gurun Tanpa Mata Air.’”
“Kita baru saja diberitahukan oleh beberapa orang asing bahwa di hutan di depan sana sedang hujan. Seberapa jauh awan hujan dibawa angin?”
“Satu yojana, tuan.”
“Apakah ada diantara kalian yang melihat di atas satu pun awan hujan?”
“Tidak, tuanku.”
“Seberapa jauh kita dapat melihat kilat petir?”
“Empat atau lima yojana, tuan.”
“Apakah ada diantara kalian disini yang melihat kilat petir?”
“Tidak, tuanku.”
“Seberapa jauh seorang manusia dapat mendengar suara gemuruh petir?”
“Dua atau tiga yojana, tuanku.”
“Apakah diantara kalian disini yang mendengar suara gemuruh petir?”
“Tidak, tuanku.”
“Mereka (tadi) bukanlah manusia, melainkan para yakkha,” si pedagang bijak tadi berkata pada orang-orangnya. “Mereka berharap kita akan membuang air kita. Kemudian ketika kita lemah dan tidak berdaya, mereka akan kembali untuk memakan kita. Karena pedagang muda yang pergi mendahului kita bukanlah orang dengan akal sehat, kemungkinan besar dia telah ditipu oleh yakkha-yakkha itu. Kita mungkin saja akan menemukan kereta-kereta mereka utuh dengan barang-barang bawaannya. Kita mungkin saja akan melihat mereka hari ini. Mari kita segera pergi secepat yang kita bisa, tanpa membuang setetes air pun!”
Seperti yang sudah diperkirakan si pedagang tadi, rombongannya segera menemukan lima ratus kereta bersama dengan tulang belulang manusia dan hewan yang berserakan di semua arah. Dia menyuruh orang-orangnya untuk membentuk kereta-keretanya dalam posisi lingkaran, merawat lembu-lembu, dan menyiapkan makan malam bagi mereka semua. Setelah semua hewan dan manusia tidur dengan aman, si pedagang dan orang-orang andalannya, dengan pedang di tangan, berjaga sepanjang malam.
Ketika hari menjelang pagi, si pedagang mengganti kereta jeleknya dengan kereta yang lebih kokoh dan menukar barang-barang dagangan biasanya dengan barang-barang dagangan yang lebih berharga dari kereta-kereta yang telah ditinggalkan tersebut. Pada saat dia tiba di kota tujuannya, dia mampu menukar barang-barang dagangannya dengan tiga sampai empat kali lipat harga awalnya. Dia pun kembali ke kota asalnya tanpa kehilangan satu orang pun pengikutnya.
Cerita ini pun berakhir, Buddha berkata, “Demikianlah, perumah tangga, bahwa di suatu waktu di masa lampau, si bodoh datang membawa bencana, sedangkan mereka yang memegang kebenaran akan terhindar dari yakkha-yakkha, mencapai tujuan mereka dengan selamat, dan dapat kembali ke rumah mereka.”
“Berpegang pada kebenaran tidak saja membawa kebahagiaan hingga kelahiran kembali di
alam Brahma 3, tetapi juga membawa pada pencapaian tingkat kesucian Arahat. Mengikuti ketidakbenaran berujung pada kelahiran kembali entah di empat alam sengsara, atau di dunia manusia dengan keadaan yang tidak menguntungkan.” Setelah Buddha menyatakan Empat Kebenaran Mulia, kelima ratus siswa tadi berhasil mencapai buah Pemasuk Arus.
Buddha Gotama kemudian mengakhiri khotbahNya dengan menjelaskan identitas Kelahiran sebagai berikut: “Si pedagang bodoh tersebut adalah
Devadatta 4, dan orang-orangnya adalah para pengikut Devadatta. Orang-orang pedagang bijak adalah pengikut Buddha, dan Aku sendiri adalah pedagang bijaksana tersebut.”
Catatan:
1. Uposatha adalah hari dimana bulan penuh, bulan baru, atau bulan setengah penuh, dimana umat Buddha sering menjalankan delapan sila.
2. Yojana: satuan jarak, sekitar tujuh mil.
3. Alam Brahma merujuk pada surga yang paling tinggi, dimana makhluk-makhluknya memancarkan cahaya berkah.
4. Devadatta adalah sepupu Buddha. Dia mencoba untuk membunuh Buddha beberapa kali tetapi selalu gagal.
http://jatakakatha.wordpress.com/category/kisah-jataka/